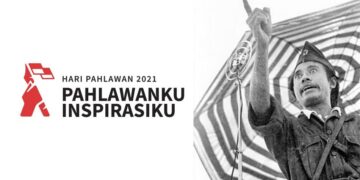Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap temuan mengejutkan: dana pemerintah pusat dan daerah senilai Rp653,4 triliun mengendap di perbankan per Agustus 2025, dengan Rp285,6 triliun berbentuk deposito berjangka. Angka ini menjadi sorotan tajam karena mencerminkan paradoks fiskal—pemerintah memiliki uang berlimpah namun daya serap anggaran rendah, sementara di sisi lain terus menambah utang untuk membiayai pembangunan.
Dalam acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism On 8% Economic Growth” di Jakarta pada Kamis (16/10/2025), Purbaya menegaskan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dana yang menganggur tersebut. Ia mencurigai adanya praktik permainan bunga dan inefisiensi sistemik dalam pengelolaan keuangan negara.
Dana pemerintah yang mengendap di deposito bank menciptakan kerugian ganda—pemerintah membayar bunga obligasi 6% untuk pinjaman, sementara hanya menerima return deposito 3-4%. Setiap Rp100 triliun yang menganggur berpotensi merugikan negara Rp2-3 triliun per tahun dari selisih bunga.
Highlights
Total dana pemerintah pusat dan daerah yang mengendap: Rp653,4 triliun (Agustus 2025)
Deposito berjangka pemerintah pusat: Rp285,6 triliun, naik Rp81,4 triliun dalam 8 bulan dari Desember 2024
Dana pemda di perbankan: Rp254,3 triliun, melonjak 176% dari Rp92 triliun (Desember 2024)
Menkeu mencurigai praktik “main bunga” dan akan investigasi asal-usul dana
Kerugian potensial negara dari negative interest margin: Rp5,7-8,6 triliun per tahun
Anatomi Dana Mengendap: Rp653 Triliun yang Tidak Bergerak
Komposisi dana pemerintah yang parkir di perbankan per Agustus 2025 terbagi dalam tiga kategori: giro sebesar Rp357,4 triliun (54,7%), deposito berjangka Rp285,6 triliun (43,7%), dan tabungan Rp10,4 triliun (1,6%). Dari total Rp653,4 triliun tersebut, Rp399 triliun berasal dari pemerintah pusat dan Rp254,4 triliun dari pemerintah daerah.
Yang paling menarik perhatian adalah lonjakan deposito berjangka pemerintah pusat. Dari posisi relatif stabil di kisaran Rp204 triliun pada Desember 2023 dan 2024, angka ini melonjak menjadi Rp285,6 triliun hanya dalam delapan bulan. Pertumbuhan sebesar Rp81,4 triliun atau 40 persen ini memicu pertanyaan mendasar dari Menkeu: “Uang apa itu?”
Purbaya mengungkapkan skeptisisme terhadap jawaban yang diterimanya dari jajaran Kemenkeu. Saat menanyakan asal-usul dana, jawabannya tidak memuaskan. Ia bahkan menyatakan yakin bawahannya mengetahui informasi tersebut namun enggan mengungkapkannya. Kecurigaan mengarah pada kemungkinan dana tersebut berasal dari lembaga-lembaga di bawah kementerian seperti LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) atau entitas lain yang menempatkan dana dalam deposito untuk memperoleh bunga.
Transparansi menjadi isu krusial. Secara sistem, setiap dana pemerintah seharusnya memiliki kode identifikasi tersendiri di perbankan, memudahkan penelusuran. Namun faktanya, bahkan dana yang tercatat di Bank Indonesia pun statusnya masih belum sepenuhnya jelas. Purbaya berjanji investigasi akan mencakup seluruh bentuk simpanan, tidak terbatas pada deposito, untuk memastikan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga: Kebijakan Dana 200T Kemenkeu: Dampak ke Ekonomi Indonesia 2025
Paradoks Fiskal: Bayar Bunga Mahal, Terima Return Rendah
Inti kritik Purbaya terletak pada negative interest margin yang merugikan negara. Pemerintah saat ini membayar bunga obligasi negara sekitar 6 persen per tahun untuk membiayai defisit APBN. Di sisi lain, deposito bank hanya memberikan return 3-4 persen per tahun—bahkan bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Mandiri hanya menawarkan bunga deposito 2,5-3,5 persen per Oktober 2025 setelah Bank Indonesia menurunkan BI Rate menjadi 4,75 persen.
Kalkulasi kerugian sangat signifikan. Dengan deposito sebesar Rp285,6 triliun dan asumsi selisih bunga 2-3 persen, negara berpotensi rugi Rp5,7-8,6 triliun per tahun. Purbaya menganalogikan: “Saya ngutang, karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dari bunga yang saya bayar untuk obligasi. Pasti saya rugi kalau gitu.”
Kerugian ini bersifat opportunity cost murni—uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, atau bahkan untuk mengurangi utang negara, justru parkir di deposito dengan return di bawah biaya utang. Ini menciptakan lingkaran setan: pemerintah terus menambah utang karena anggaran tidak terserap, sementara dana yang ada malah mengendap tidak produktif.
Situasi semakin ironis mengingat pemerintah sedang mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dana yang menganggur ini, jika dialirkan ke sektor produktif melalui kredit perbankan atau belanja pemerintah, dapat memberikan multiplier effect yang jauh lebih besar bagi perekonomian.
Dana Pemda Melonjak 176%: Indikasi Rendahnya Penyerapan Anggaran
Jika dana pemerintah pusat mengejutkan, kondisi dana pemerintah daerah lebih mengkhawatirkan. Simpanan pemda di perbankan mencapai Rp254,3 triliun per Agustus 2025, melonjak drastis 176 persen dari Rp92 triliun pada Desember 2024 dan 145 persen dari Rp103,9 triliun pada Desember 2023.
Komposisi dana pemda: giro Rp188,9 triliun (74,3%), deposito berjangka Rp57,5 triliun (22,6%), dan tabungan Rp8 triliun (3,1%). Lonjakan dana pemda yang tidak terserap ini menjadi salah satu justifikasi Kemenkeu untuk memangkas Transfer Ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 dari usulan awal Rp864 triliun menjadi Rp693 triliun—pemotongan sebesar Rp171 triliun atau 20 persen.
Purbaya menceritakan reaksi kepala daerah: “Tahun depan anggaran ada efisiensi di mana anggaran ke daerah saya kurangi. Mereka datang ke saya marah-marah, wah kenapa dipotong? Mereka enggak kekurangan uang, bahkan kelebihan.” Pada 7 Oktober 2025, sebanyak 18 gubernur menyambangi Kemenkeu untuk memprotes pemotongan TKD, dengan dalih beban belanja PPPK dan pembangunan infrastruktur.
Namun data menunjukkan argumen berbeda. Jika pemda memiliki Rp254,3 triliun yang mengendap di bank, pertanyaannya sederhana: mengapa masih membutuhkan dana transfer lebih besar? Purbaya menegaskan akan menambah TKD kembali pada pertengahan 2026 jika realisasi belanja daerah baik, efisien, dan tanpa kebocoran.
Baca Juga: Rencana Ekspansi, Begini Respon 5 Bank BUMN Setelah Terima Dana 200T
Dugaan “Main Bunga”: Investigasi Menyasar LPDP dan Entitas Kementerian
Salah satu target investigasi adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mengelola dana abadi sebesar Rp154,11 triliun per Agustus 2025. Data menunjukkan LPDP menempatkan 31,94 persen atau Rp50,57 triliun dalam deposito di 21 bank mitra melalui sistem lelang. Sisanya tersebar di obligasi negara (62,96% atau Rp99,68 triliun), obligasi korporasi BUMN (1,72% atau Rp2,72 triliun), dan SRBI Bank Indonesia.
LPDP memiliki mandat menginvestasikan dana abadi untuk menghasilkan yield yang kemudian digunakan membiayai beasiswa dan riset—dana pokok tidak boleh dibelanjakan. Hingga Agustus 2025, LPDP mencatatkan yield 7,11 persen, di atas target yang ditetapkan. Pertanyaannya: apakah penempatan dana LPDP di deposito masuk dalam kategori Rp285,6 triliun deposito pemerintah pusat yang diselidiki Purbaya?
Jika ya, ini menimbulkan isu klasifikasi. Dana abadi LPDP seharusnya tercatat terpisah karena bersifat investasi jangka panjang dengan tujuan menghasilkan return, berbeda dengan dana operasional pemerintah yang seharusnya liquid untuk kebutuhan belanja. Purbaya mengindikasikan: “Bisa saja LPDP dan seterusnya. Harusnya sih terpisah kan.”
Kecurigaan “main bunga” yang dimaksud Purbaya merujuk pada praktik di mana pejabat atau entitas tertentu sengaja menempatkan dana pemerintah di deposito untuk memperoleh bunga, padahal dana tersebut seharusnya dibelanjakan atau ditempatkan di instrumen yang lebih menguntungkan negara. Dalam sistem perbankan, deposito besar umumnya mendapat negosiasi rate khusus—ini membuka celah conflict of interest jika tidak diawasi ketat.
Konteks Lebih Luas: Efisiensi Anggaran dan Cash Management
Temuan dana mengendap ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari narasi besar kebijakan fiskal Purbaya yang berbeda dari pendahulunya Sri Mulyani Indrawati. Jika Sri Mulyani menerapkan efisiensi dengan memangkas anggaran K/L (Kementerian/Lembaga) berdasarkan persentase tertentu melalui PMK 57/2025, Purbaya mendefinisikan efisiensi sebagai optimalisasi cash management.
“Efisiensi saya gak motong anggaran. Anggarannya sama, sama kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau anda lebih pintar memanage uang. Ini cash management,” tegasnya. Filosofi Purbaya: dana yang menganggur akan ditarik dan dialokasikan ke program prioritas atau digunakan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat utang baru.
Implementasi nyata terlihat dari keputusan mencairkan dana SAL (Saldo Anggaran Lebih) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara pada September 2025. Tujuannya: meningkatkan likuiditas perbankan agar bisa menyalurkan kredit lebih agresif, terutama ke UMKM, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pendekatan ini memang berbeda. Alih-alih memblokir atau membintangkan anggaran, Purbaya memberikan tenggat waktu kepada K/L untuk menyerap anggaran hingga akhir Oktober 2025. Jika tidak terserap, dana ditarik tanpa kompromi. “Kalau nganggur besar-besar, saya ambil!” tegasnya. Kebijakan ini sempat memicu kontroversi, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis yang realisasinya baru 29 persen dari pagu Rp71 triliun.
Implikasi terhadap Perbankan dan Ekonomi Makro
Dari perspektif perbankan, dana pemerintah Rp653 triliun yang mengendap di bank sebenarnya menjadi sumber likuiditas penting. Deposito berjangka Rp285,6 triliun memberikan dana murah kepada bank untuk disalurkan sebagai kredit. Namun, ini menciptakan ketergantungan: jika pemerintah tiba-tiba menarik dana dalam jumlah besar, bank bisa mengalami pressure likuiditas.
Kebijakan Purbaya memindahkan SAL Rp200 triliun dari BI ke Himbara justru menunjukkan strategi mengalirkan dana idle ke perbankan—namun dengan syarat: dana harus disalurkan ke sektor riil, bukan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Ini menciptakan ekspektasi: suku bunga kredit harus turun, mendorong investasi dan konsumsi.
Per Oktober 2025, respons perbankan terhadap penurunan BI Rate menjadi 4,75 persen masih lambat. Suku bunga deposito BRI turun 0,35-0,50 persen, sementara Bank Mandiri dan BNI belum melakukan penyesuaian signifikan. Suku bunga kredit pun masih di kisaran 9,13 persen per Agustus 2025, hanya turun 7 basis poin dari awal tahun—jauh dari ekspektasi pemerintah.
Di sisi ekonomi makro, dana pemerintah yang menganggur menghambat velocity of money. Uang yang seharusnya berputar di ekonomi melalui belanja pemerintah, malah parkir di deposito. Ini menjelaskan mengapa, meski APBN 2025 ekspansif dengan defisit 2,29 persen PDB, dampak stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi belum optimal—karena realisasi belanja rendah.
Risiko dan Outlook: Antara Transparansi dan Political Economy
Investigasi Purbaya terhadap dana Rp653 triliun berpotensi membuka kotak Pandora. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, atau conflict of interest dalam penempatan dana, ini bisa memicu guncangan institusional. Namun, jika investigasi berjalan transparan, ini justru peluang memperbaiki tata kelola keuangan negara.
Dari sisi political economy, tekanan terhadap pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran menciptakan trade-off. Kepala daerah terjepit antara tuntutan efisiensi dari pusat dengan kebutuhan belanja pembangunan dan pegawai. Pemotongan TKD Rp171 triliun memaksa pemda melakukan realokasi drastis—berpotensi mengorbankan program pembangunan jangka panjang demi memenuhi belanja operasional.
Di tingkat pusat, kebijakan Purbaya menarik dana yang tidak terserap dari K/L juga kontroversial. Anggota DPR seperti Mukhamad Misbakhun mengkritik sikap Purbaya yang dianggap terlalu intervensi ke kementerian lain. Namun Purbaya membela diri: “Saya berkepentingan memastikan anggaran saya terserap. Kalau enggak terserap, saya ambil uangnya. Itu saja.”
Untuk sisa 2025 dan menjelang 2026, beberapa skenario dapat terjadi:
Skenario Optimis: Investigasi berjalan transparan, ditemukan inefisiensi yang diperbaiki, penyerapan anggaran meningkat, dana mengendap berkurang, dan ekonomi tumbuh lebih kuat karena uang berputar produktif.
Pesimis: Investigasi terhambat resistensi birokrasi, inefisiensi berlanjut, pemotongan TKD memicu ketegangan pusat-daerah, dan pertumbuhan ekonomi stagnan karena konsumsi pemerintah rendah.
Skenario Realistis: Perbaikan parsial terjadi, beberapa K/L dan pemda meningkatkan penyerapan, namun struktural problem seperti kapasitas perencanaan dan pengadaan yang lemah masih menghambat. Dana mengendap berkurang tapi tidak drastis—turun menjadi Rp500-550 triliun pada akhir tahun.
Dari Idle Cash ke Productive Capital
Kasus dana pemerintah Rp653 triliun mengendap di bank memberikan pelajaran penting tentang cash management dalam pengelolaan keuangan publik. Memiliki kas besar bukan indikator positif jika tidak digunakan produktif. Yang diperlukan:
- Sistem pelaporan real-time untuk semua dana pemerintah—pusat, daerah, maupun entitas di bawah kementerian—dengan kode identifikasi jelas agar mudah dilacak dan diaudit.
- Sanksi tegas bagi K/L dan pemda yang konsisten gagal menyerap anggaran—bukan hanya pemotongan anggaran tahun berikutnya, tapi juga evaluasi kemampuan manajerial pejabat.
- Reformasi sistem pengadaan yang lebih cepat dan efisien, sehingga belanja tidak menumpuk di akhir tahun—fenomena yang selama ini menjadi ciri khas serapan APBN dan APBD.
- Treasury management profesional yang mampu mengoptimalkan penempatan dana pemerintah—jika harus ditempatkan sementara di pasar uang, minimal memperoleh return yang setara atau lebih tinggi dari biaya utang pemerintah.
- Transparansi publik melalui dashboard yang dapat diakses masyarakat, menampilkan secara real-time posisi kas pemerintah, realisasi belanja, dan status penyerapan per K/L dan pemda—meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan.
Tantangan terbesar bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada kapasitas institusional untuk mengeksekusi program dengan cepat, tepat, dan akuntabel. Dana Rp653 triliun yang mengendap adalah gejala, bukan penyakit. Penyakit sebenarnya adalah lemahnya perencanaan, lambatnya pengadaan, dan kurangnya insentif bagi birokrat untuk bekerja cepat tanpa risiko salah.
Purbaya menutup investigasinya dengan warning tegas: “Jangan sampai uang saya nganggur di perbankan.” Pertanyaannya sekarang: apakah birokrasi siap bertransformasi dari mindset menimbun menjadi mindset mengeksekusi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan keberhasilan agenda ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai pertumbuhan 8 persen yang diimpikan.
Catatan Metodologi:
Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada acara “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” (16/10/2025), data Kementerian Keuangan per Agustus 2025, laporan LPDP, data suku bunga perbankan dari Bank Indonesia dan bank-bank BUMN, serta regulasi terkait efisiensi anggaran (Inpres 1/2025, PMK 56/2025). Analisis kerugian opportunity cost dihitung berdasarkan rata-rata bunga obligasi negara 6% dan bunga deposito 3-4% per Oktober 2025.
Sumber: Detik Finance, Voi.id, Liputan6, CNN Indonesia, Kompas, CNBC Indonesia, Antara News, Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, LPDP, per 17 Oktober 2025.

Seorang Mahasiswa S2 Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tertarik pada investasi seperti saham, deposito dan Instrumen lainnya.